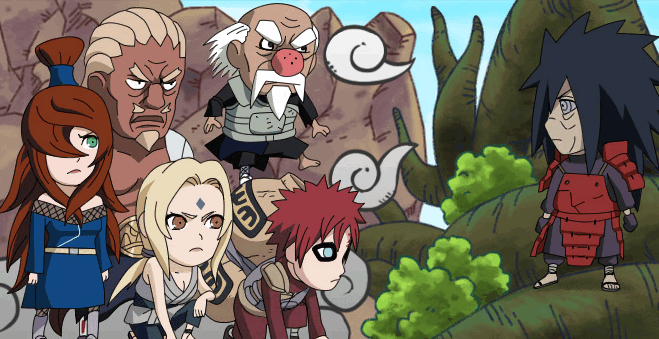Lembar Kerja Siswa tiba-tiba jadi ‘primadona’ berita. Cerita rakyat–tapi entah benar ini cerita rakyat apa bukan–berjudul Bang Maman dari Kalipasir sontak dipermasalahkan karena mengandung kata berkonotasi negatif ‘istri simpanan’. Masalahnya meskipun kata itu sudah lazim kita dengar di televisi, radio, maupun surat kabar, kata tak elok itu justru menyelip dalam cerita rakyat tadi yang ditujukan untuk pembaca sasaran siswa kelas II SD. Kasus ini merembet pada LKS-LKS lain, termasuk juga kesalahan menyajikan kunci jawaban pada soal tentang ideologi negara.
Masalah ini pun melebar jadi ke mana-mana. Soal standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang kelirulah, termasuk ketidakcermatan pemilihan contoh cerita rakyat. Soal LKS adalah bukan buku layaklah. Siapa yang mau mengklaim bahwa LKS bukanlah buku? LKS atau dalam istilah bahasa Inggris disebut workbook lazim digunakan sebagai buku pendamping buku ajar. LKS kadang berupa lembaran-lembaran berisi soal-soal untuk dikerjakan siswa dan kadang dapat dirobek per lembar untuk dinilaikan. Di dalamnya terdapat materi sebagai pengantar, tetapi tidak mendalam.
Namun, LKS menjadi salah kaprah jika diposisikan sebagai buku ajar karena kedalamannya sangat kurang seperti halnya modul dalam lokakarya ataupun pelatihan. Adapun pendapat mengatakan LKS bukan buku juga dapat dibantah dengan definisi buku yang dinyatakan Unesco berikut ini.
Apa yang disebut buku? Unesco pada awal 1970-an mengeluarkan data statistik tentang perbukuan dunia. Data ini diperlukan untuk mengukur pengaruh buku terhadap perkembangan ekonomi dan budaya pada suatu negara, khususnya negara Dunia Ketiga. Hasil pendataan ini hendak digunakan untuk mengurangi angka buta huruf pada masyarakat dunia. Karena itu, Unesco pun membuat batasan buku sebagai berikut:
lembaran-lembaran kertas yang bercetak;
kertas-kertas bercetak itu digabungkan menjadi satu dalam bentuk jilidan;
kertas-kertas bercetak dan berjilid itu memunyai kulit (sampul) yang biasanya menggunakan kertas lebih tebal dan berbeda jenisnya dengan teks;
kertas-kertas bercetak itu mengandung lebih dari 49 halaman;
cetakannya tidak dilakukan dalam masa-masa tertentu dan tidak berurutan dengan penerbitan yang lain (bukan berkala).
Dengan batasan ini, Unesco pun mudah melakukan klasifikasi penerbitan buku pada suatu negara. Batasan Unesco ini tentu tidak terlalu lengkap karena tidak pula menyebutkan ukuran dan bentuk terbitan yang disebut buku itu seperti apa. Unesco hanya ingin membedakan buku dari terbitan berkala (media massa) serta terbitan lain seperti brosur, laporan, dan katalog yang tidak dapat disebut buku. Unesco kemudian menambahkan kriteria baru untuk buku yaitu diterbitkan sekurang-kurangnya 50 eksemplar dan dijual terbuka—kriteria ini malah mempersulit mereka yang hanya menerbitkan buku secara terbatas.
Batasan buku tersebut boleh jadi berbeda di setiap negara. Di Indonesia lembaga akademik seperti Lembaga Administrasi Negara tampaknya mengacu pada batasan Unesco untuk mendefinisikan karya tulis ilmiah berbentuk buku. Karena itu, muncul pula syarat tambahan seperti buku wajib ber-ISBN dan wajib pula diedarkan atau dijual di toko-toko buku. Ketentuan ini harus dijalankan para widyaiswara yang hendak menerbitkan buku.
Namun, kalangan penerbit Indonesia ada yang menerbitkan buku kurang dari 49 halaman yang dikategorikan buku anak. Buku anak ada yang terbit 8, 16, 24, dan 32 halaman (semuanya kelipatan 8 atau 16). Buku-buku umum untuk pembaca dewasa di Indonesia umumnya terbit dalam kisaran 80—160 halaman. Buku ajar perguruan tinggi dapat berkisar 200 halaman lebih.
Saya memandang kasus ini adalah kasus keteledoran editing belaka, bukan mempermasalahkan LKS tidak pantas menjadi buku yang digunakan untuk belajar mengajar. LKS harus ditempatkan pada penggunaannya untuk menguji kemampuan siswa secara harian atau periode tertentu dalam memahami sebuah materi pelajaran. LKS mendukung penggunaan buku ajar di sekolah. Nah, masalahnya karena LKS ini seperti dianggap ‘ringan dan lucu’ apakah perlu mempekerjakan seorang editor profesional untuk mengeditnya?
Ditengarai bahwa banyak penerbit LKS itu memang menjalankan usahanya sebagai usaha rumahan (home industry) atau usaha kecil menengah. Modal utama mereka memang jaringan guru-guru di sekolah. LKS ini seolah menjadi alternatif penggunaan buku ajar karena dianggap lebih murah. Banyak LKS menggunakan kertas jenis kertas koran (CD) dan dicetak cukup dengan mesin cetak offset TOKO. Jilidnya pun cukup menggunakan saddle stiching (jahit kawat). Penulisnya melibatkan guru-guru ataupun mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi. Di sinilah kerap demi efisiensi, para penulis juga merangkap sebagai editor. Karena itu, LKS seperti bahan ajar yang ‘murah meriah’ dan yang penting sesuai dengan kurikulum.
Pada penerbit LKS yang lebih besar dengan skala industri, mungkin saja mempekerjakan para editor, baik sebagai karyawan maupun secara lepas. Memang dalam skala UKM, banyak penerbit tadi tidak tergabung di dalam Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) sehingga mereka pun menjalankan bisnis penerbitan dengan nalar dan wawasannya saja tanpa peduli tentang aspek editorial yang selalu menjadi fokus pembinaan IKAPI untuk para penerbit anggotanya.
Editing buku untuk sekolah ini tidaklah gampang. Sang editor memerlukan kecermatan tingkat tinggi, terutama dalam menjaga aspek editing, yaitu
* keterbacaan dan kejelahan;
* ketaatasasan;
* kebahasaan;
* ketelitian data dan fakta;
* kelegalan dan kesopanan-kepatutan.
Adapun di dalam buku-buku untuk belajar itu ada aspek penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar berupa materi, pengayaan materi (enrichment), soal-soal, rangkuman materi, dan tentunya kreativitas penulis yang menjadikan bukunya berbeda dengan buku lain. Semunya menuntut kebenaran dan kepatutan dari sisi materi serta penyajian.
Adalah penting bahwa seorang editor tidak hanya mengedit dengan akalnya, tetapi juga dengan perasaannya. Editing yang termasuk sulit adalah editing pada nilai rasa suatu materi dikaitkan dengan pembaca sasaran, apalagi pembacanya anak-anak. Karena itu, tidak salah jika Romo Mangun mengatakan bahwa ‘dalam ranah tulis-menulis yang paling sulit adalah menulis cerita anak dan di ujung ekstremnya yang paling mudah adalah menulis skripsi’.
Tingkat kesulitan menulis buku untuk anak SD lebih tinggi daripada menulis buku untuk anak SMP atau SMA. Penggunaan materi dan pemilihan bahan ajar seperti wacana (berita, cerita, artikel, dsb.) harus memperhatikan konteks pemikiran anak. Nah, terkadang sang penulis pun keliru memilihkan cerita anak yang berkualitas dan tepat untuk anak. Cerita rakyat tidak selalu cocok untuk anak karena cerita rakyat awalnya berkembang sebagai foklor dari mulut ke mulut sekadar untuk menghibur. Dongeng pun yang tercipta pada masa lampau tidak selalu identik ditujukan untuk pembaca anak-anak karena di Indonesia ada dongeng-dongeng yang sangat sensitif untuk alam pikiran anak, misalnya Sangkuriang dari Jawa Barat yang berniat menikahi ibu kandungnya sendiri.